Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
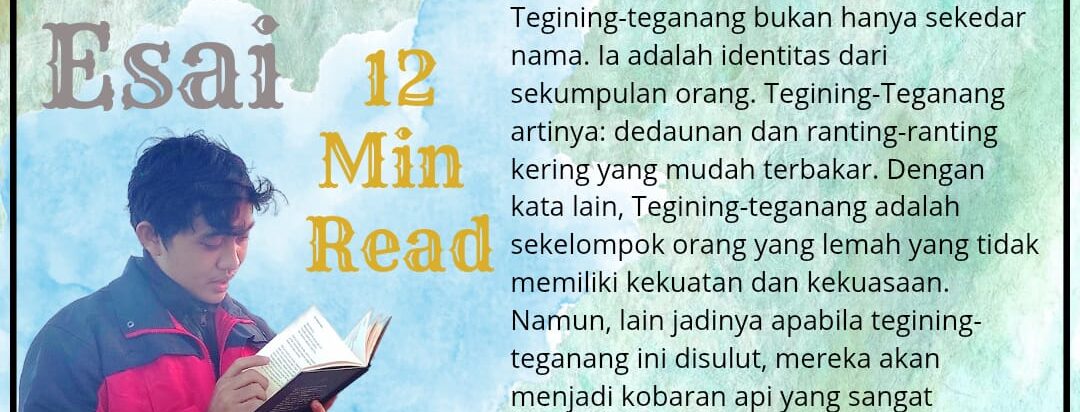
Oleh : Lalu Muhammad Ilham Fajri
Tahun 2024 lalu, saya nyantrik ke kediaman Mamiq Rahme (budayawan Sasak) di Desa Penujak. Dalam kesempatan tersebut, beliau banyak bercerita tentang filosofi-filosofi hidup kebudayaan orang Sasak. Filosofi tersebut terselip dalam setiap aspek kebudayaan sasak baik berupa benda-benda peninggalan, ritual, maupun kesenian. Salah satu yang beliau ceritakan pada waktu itu adalah lagu rakyat “Tegining-Teganang” , lagu yang populer di Lombok. Saya menghapal lagu ini sejak duduk di Sekolah Dasar. Liriknya yang ringkas dan iramanya yang membawa keriangan membuat lagu ini mudah di hapal. Di balik lagu tersebut, terselip gagasan mendalam menyeru tajam untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi. Menegakkan demokrasi, artinya tiada lain adalah menegakkan suara rakyat.
Demokrasi adalah konsep atau cara hidup yang menekankan kesetaraan hak, kewajiban, dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Demokrasi juga bisa diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana rakyat ikut berperan dalam pengambilan keputusan melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Jeff Haynes[1] membagi penerapan demokrasi ke dalam tiga model. Pertama, demokrasi formal, yaitu sistem yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemerintah melalui pemilu yang diadakan secara berkala sesuai dengan aturan tertentu. Kedua, demokrasi superfisial, yang sering ditemukan di negara-negara berkembang. Secara tampilan, sistem ini terlihat demokratis, tetapi pada kenyataannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang sejati. Demokrasi ini disebut juga demokrasi berintensitas rendah, di mana demokrasi hanya menjadi simbol tanpa mengubah struktur politik secara mendasar. Demokrasi ini hanya menekankan aspek prosedural tanpa mengutamakan nilai-nilai fundamental. Ketiga, demokrasi substantif, yang dianggap sebagai bentuk demokrasi dengan kualitas terbaik. Dalam model ini, semua lapisan masyarakat, termasuk rakyat biasa, kelompok miskin, minoritas, anak muda, dan perempuan, memiliki hak untuk menyuarakan kepentingan mereka dalam agenda politik negara.
Pesan dalam Lirik Lagu Tegining Teganang
Lirik Lagu Tegining Teganang
Leq jaman laeq Araq sopoq cerite /Inaq Tegining Amaq Teganang aranne/ Pegaweanne ngaret sampi lek tengaq rau/ Sampin sai tekujang-kujing leq tengaq rau?/ Inaq tegining amaq Teganang epenne/ Ongkat dengan tegining Teganang lueq cerite/ Ngalahin datu sak beleq beleq ongkatne
Lirik lagu Tegining-teganang berisi sebuah kisah yang menceritakan kehidupan Inaq Tegining Amaq Teganang. Terdapat tujuh larik dalam lagu ini dan dibalik larik-larik tersebut dapat kita temukan pesan sekaligus peringatan tentang demokrasi. Berikut lirik lagu ”Tegining teganang” dan makna dibaliknya:
“Lek jaman laek arak sopok cerite“
“ Lek jaman laek arak sopok cerite” artinya pada zaman dahulu ada sebuah cerita. Lirik pembuka lagu ini cukup menarik. Mamiq Rahme langsung melempar pertanyaan kepada kami, “apakah benar yang dimaksud ‘lek jaman laek’ pada lirik lagu ini merujuk pada zaman dahulu sebelum lagu ini diciptakan atau yang dimaksud adalah masa depan yang akan datang?” Inilah seninya orang-orang tua zaman dahulu. Karya sastra baik lagu maupun cerita rakyat selalu mengandung pesan baik berupa peringatan maupun kritikan namun pesan tersebut tidak disampaikan secara blak-blakan tujuannya untuk menghindari ketersinggungan dan agar pesan tersebut lebih mudah diterima. Orang tua zaman dahulu terbiasa mendidik anak-anaknya melalui simbol-simbol sehingga yang bisa memahami pesan mereka adalah generasi penerus yang peka terhadap simbol-simbol.
Lagu tegining-teganang ini menceritakan tentang penguasa yang lalim terhadap rakyatnya. Catatan kisah mengenai penguasa yang lalim sangat banyak dan terus terjadi sepanjang sejarah. Dengan tidak langsung pencipta lagu ini tidak hanya bermaksud menceritakan sejarah tetapi juga memberikan peringatan kepada generasi yang akan datang akan adanya penguasa lalim yang menindas rakyat. Dengan demikian konsep waktu yang disampaikan dalam lirik awal lagu ini dapat dibaca secara terbalik sehingga “lek zaman laek” yang dimaksud adalah “lek mase sak muri” (di masa yang akan datang). Jika kita refleksikan dengan realitas saat ini, benarlah peringatan tersebut bahwasanya kisah penguasa yang lalim masih terjadi sampai saat ini.
Inaq Tegining Amak Teganang arane
Tegining-teganang bukan hanya sekedar nama. Ia adalah identitas dari sekumpulan orang. Melalui penuturan Mamiq Rahme saya baru tau bahwa arti sebenarnya dari Tegining-Teganang ini adalah dedaunan dan ranting-ranting kering yang mudah tersulut dan terbakar. Dengan kata lain, Tegining-teganang adalah sekelompok orang yang lemah yang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Penyebutan Inaq dan Amaq memperkuat identitas tegining-teganang sebagai orang kelas bawah karena dalam konsep kebangsawanan (Triwangsa) Inaq dan Amaq adalah penyebutan bagi orang tua yang berasal dari kalangan yang paling rendah tingkat kebangsawanannya. Meskipun mereka diibaratkan hanya sekedar ranting dan dedaunan kering, lain jadinya apabila mereka berhasil disulut, mereka akan menjadi kobaran api yang sangat menakutkan. Kobaran api yang tak kenal tuan, ia akan melalap apa saja yang dilaluinya. Tegining-teganang itu adalah rakyat.
“Pegaweane ngaret sampi lek tengak rau“
Pekerjaan dari Tegining Teganang adalah menenggala sapi di tengah sawah. Mereka adalah buruh di ladang. Mereka dibayar dari hasil pekerjaannya menggemburkan ladang pertanian. Mereka hidup dari hasil-hasil bumi. Setiap hari mereka berdoa meminta kesuburan, setiap hari mereka merawat tanaman-tanaman dan ternak-ternak mereka. Mereka bersahabat dengan alam dan dekat dengan Tuhan. Pekerjaan Tegining Teganang sebagai seorang yang menenggala sapi ini mewakili rakyat kelas bawah yang hidup dengan hasil keringat. Kekuasaan mereka hanya sekedarnya untuk mengurusi ladang, memutar roda mesin pabrik, berjualan kecil-kecilan. Mereka adalah rakyat kelas bawah yang seringkali namanya dijual oleh para penguasa dengan mengatakan “demi rakyat” namun seringkali hak-hak mereka diabaikan bahkan dieksploitasi.
“Sampin sai tekujang-tekujing lek tengak rau? Inaq Tegining Amak Teganang epene“
Sapi siapa yang dizolimi di tengah ladang? Inaq Tegining dan Amak Teganang yang punya. Lirik ini menyiratkan bahwa para penguasa lalim serungkali menzolimi rakyat salah satunya dengan menghilangkan sumber penghasilan mereka. Dalam kehidupan saat ini, kedzoliman terhadap Sapi Tegining Teganang dapat diartikan sebagai pengalih fungsian lahan, pembabatan hutan, penutupan pabrik dan segala upaya lain yang dilakukan para penguasa untuk memperkaya diri dan berimbas penuh kepada rakyat kelas menengah ke bawah.
“Ongkat dengan tegining-teganang luek cerite“
Sudah banyak orang yang mengisahkan keberanian Tegining-Teganang. Cerita keberanian Tegining Teganang ini terus disebarkan, dinyanyikan sebagai peringatan kepada para penguasa bahwa Tegining Teganang (rakyat) dapat mengalahkan penguasa lalim itu. Tegining Teganang memiliki senjata pamungkas untuk mengalahkan penguasa. Senjata yang membuat para penguasa takut, sebagaimana mereka takut terhadap kobaran api yang menyambar-nyambar.
“Ngalahin datu sik belek-belek ongkatne“
Senjata pemungkas untuk mengalahkan penguasa lalim itu tidak lain adalah “ongkat” atau Kata-kata. Penguasa lalim, sangat takut apabila rakyat mampu bersuara menyampaikan fakta bahwa selama ini mereka ditindas, selama ini penguasa bertindak dzolim, selama ini penguasa menyembelih hak-hak rakyat, selama ini penguasa membungkam suara-suara rakyat. Tegining Teganang mengajak setiap golongan rakyat untuk berteriak, menyampaikan suaranya, membangun wacana berdasarkan rasio dan fakta. Tegining Teganang adalah rakyat yang bernurani dan berani dengan lantang menyuarakan kebenaran.
Demokrasi Hibrid di Era Informasi Digital
Sejak merdeka, Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan demokrasi. Meski telah lama menyatakan diri sebagai negara demokratis, nyatanya Indonesia masih berjuang untuk membangun sistem yang stabil dan matang. Di era digital saat ini, kebebasan informasi membuka peluang besar, tetapi juga membawa tantangan baru bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kemudahan untuk mengakses dan memproduksi informasi di era digital di satu sisi menjadi peluang bagi rakyat untuk menyuarakan hak-haknya. Melalui web berita online dan berbagai sosial media, masyarakat umum dapat menyuarakan keresahannya, ketidakpuasannya dan kekesalannya akan berbagai kebijakan dan tindakan korup pemerintah yang merugikan rakyat.
Di sisi lain, terdapat tantangan bagi demokrasi di Indonesia di era informasi digital. Salah satu tantangan demokrasi di era digital adalah fenomena buzzer politik. Dengan memanfaatkan media sosial, buzzer dapat membentuk opini publik, menyebarkan propaganda, dan bahkan menyebarluaskan informasi yang belum tentu benar. Kehadiran mereka sering kali membuat ruang diskusi politik menjadi tidak sehat, karena bukannya mendorong perdebatan yang konstruktif, mereka justru memperkeruh suasana dengan narasi yang menguntungkan kelompok tertentu. Akibatnya, masyarakat bisa terjebak dalam polarisasi, sulit membedakan fakta dan opini, serta kehilangan kepercayaan pada proses demokrasi yang sehat dan transparan. Hal tersebut seringkali menimbulkan perdebatan, baku hantam di ruang cyberspace tanpa arah yang jelas, mana yang benar dan mana yang salah. Dengan demikian, solusi untuk menciptakan demokrasi yang harmonis di era digital sangat dibutuhkan. Solusi ini diharapkan mampu mewujudkan cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetap menjaga jati diri, sekaligus mengikuti perkembangan zaman.
Yasraf Amir Piliang yang dikenal sebagai seorang filosof, pemikir kebudayaan dan pengamat sosial menjelaskan, demokrasi di Indonesia sulit berjalan optimal karena belum memenuhi beberapa pra-kondisi yang ideal diantaranya: Pertama, kurangnya ruang diskusi yang sehat membuat sulit tercapainya kesepakatan dalam konsep demokrasi. Kedua, tidak adanya persaingan ideologi yang kuat dikarenakan tidak adanya kontestasi antagonistik dalam memenangkan gagasan politik dan mencapai hegemoni.. Ketiga, institusi dan komunitas politik masih rapuh. Keempat, ideologi yang lemah. Kelima, sistem politik yang belum berjalan dengan baik. Di samping itu, politik di Indonesia sangat bergantung pada faktor ekonomi, sehingga kehilangan kemandiriannya. Ketergantungan ini menjadikan sistem politik dan mengarah pada masyarakat yang dikendalikan oleh budaya konsumtif dan kepentingan individu.[2]
Rakyat adalah jantung demokrasi. Di panggung-panggung demokrasi para politikus kerap mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan-kepentingan yang belum tentu menguntungkan rakyat. Malah, bisa jadi malah semakin mencekik rakyat. Di situlah, kata “rakyat” yang keluar dari mulut politikus hanya menjadi penanda kosong, kata yang hilang maknanya. Kata “rakyat” yang seharusnya mewakili seluruh warga negara seringkali hanya menjadi label untuk mengelabui publik. Seringkali rakyat yang dimaksud dalam frasa “demi kepentingan rakyat” hanyalah segolongan orang entah pengusaha atau pengusaha yang haus untuk memperkaya diri tanpa memperhitungkan hak-hak orang lain. Sebagaimana dikatakan Yasraf “kekuatan rakyat adalah konsep yang muatan isinya kosong, karena tidak ada ruang atau institusi nyata tempat menunjukkan kekuatan ini, kecuali melalui perwakilan”[3]. Dewan Perwakilan Rakyat yang diharapkan menjadi penyambung lidah rakyat seringkali membuat kebijakan yang berkebalikan dengan kehendak rakyat. Sehingga suara rakyat, sebagaimana dikatakan Alain Boudieu ibarat himpunan bilangan kosong, ia ada namun tak pernah berhasil diadakan (persentasi yang tak terepresentasikan). [4]
Yasraf Amir Piliang menawarkan gagasan demokrasi hibrid sebagai tawaran solusi permasalahan demokrasi di era digital. Gagasan ini merupakan gabungan antara beberapa model demokrasi yakni model demokrasi: deliberatif, otonomis, agonistik, dan tandingan, yang meskipun berbeda dalam cara dan prinsipnya, memiliki kesamaan tujuan untuk merevitalisasi kekuatan rakyat.[5]
Pertama, demokrasi deliberatif. Model demokrasi ini didasarkan pada gagasan bahwa konflik dan perseteruan antar elemen demokratis dapat diselesaikan melalui ajang dialog kritis bersama di ruang publik. Adanya media digital mempermudah dan memperluas ruang publik (cyberspace) bagi dialog-dialog kritis dan reflektif tersebut. Adanya komunikasi di ruang publik secara terbuka memungkinkan suara rakyat dengan segala multiplisitasnya akan dapat didengarkan. Mendengar berbagai pandangan yang berbeda adalah syarat utama dalam demokrasi dengan demikian dapat diambil kebijakan yang terbaik.
Kedua, demokrasi agonistik. Model ini didasari oleh gagasan bahwa demokrasi adalah sebuah medan antagonistik di mana terjadi pertarungan antar berbagai entitas kekitaan dengan kekitaan yang lainnya. Baik secara pandangan hidup, keyakinan, nilai-nilai yang sulit diikat dalam suatu konsensus bersama. Antagonisme ini perlu dirawat dan perbedaan yang ada mesti dihargai bukan dimusnahkan. Internet dapat menjadi medan pertarungan antar berbagai elemen dalam demokrasi yang memiliki perbedaan.
Ketiga, demokrasi otonomis. Model ini bertujuan untuk memastikan demokrasi berjalan dengan lancar baik pada tingkat kelompok maupun individu. Rakyat sebagai jantung demokrasi dalam model ini tidak hanya dipandang dalam satu dimensi melainkan banyak dimensi yang mencerminkan subjektivitas masing-masing individu dalam sistem demokrasi. Model demokrasi ini mendorong setiap orang atau kelompok untuk membuat wacana tentang dirinya sehingga tidak bergantung pada wacana-wacana yang dibangun di luar dirinya. Dengan demikian setiap individu terlibat aktif dalam proses demokrasi sehingga persamaan dan kebebasan rakyat dapat diwujudkan lebih total. Teknologi digital memudahkan setiap individu untuk mengekspresikan subjektivitasnya dan mewacanakan dirinya di hadapan publik.
Keempat, demokrasi tandingan. Model demokrasi ini dibangun atas rasa ketidakpercayaan terhadap kekuasaan dengan tujuan memastikan kepentingan rakyat secara menyeluruh dapat direalisasikan. Tagar #NoViralNoJustice adalah salah satu bentuk dari model demokrasi tandingan di era digital. Media sosial menjadi tempat aduan bagi rakyat sehingga dapat tersebarluas dan didengarkan oleh kalangan banyak. Reaksi dari massa yang banyak menjadi senjata untuk menandingi kekuatan penguasa.
Lagu Tegining-Teganang dan Gagasan Demokrasi Hibrid di Era Digital
Lagu tegining teganang adalah pesan dengan toaq laek bagi generasi kita saat ini dan di masa yang akan datang. Lagu perlawanan dari leluhur sasak ini sangat syarat makna dan berilian. Lagu ini dapat menjadi semangat perjuangan bagi aktivis-aktivis di tengah lumpuhnya demokrasi. Lagu ini selaras dengan tawaran Pak Yasraf mengenai demokrasi Hybrid.
Lirik “ongkat dengan tegining-teganang luek cerita” mewakili konsep demokrasi deliberatif dan otonomis. Konsep deliberatif dalam lirik tersebut adalah pentingnya gagasan di ruang publik luas agar dipahami orang banyak sebagaimana orang-orang pada zaman dahulu mengenal dan menghayati kisah perlawanan tegining-teganang. Komunikasi di ruang publik itulah cara untuk menyulut rakyat. Sedangkan konsep otonomisnya adalah perlunya pembentukan wacana sebagaimana cerita tegining teganang dibentuk dan dilagukan sehingga menjelaskan subjektivitas dari tegining-teganang sebagai subjek demokratis.
Lirik “pegwaweane ngaret sampi lek tengak rau” menggambarkan konsep demokrasi agonistik. Lirik tersebut menjelaskan posisi antagonistik dari sosok tegining teganang sebagai buruh ladang yang di sisi lain dapat dipertentangkan dengan tuan tanah (proletar vs borjuis). Saat ini, model antagonistis ini semakin meredup hal ini salah satunya dipengaruhi oleh politik bahasa zaman orde baru. Banyak pekerja saat ini yang tidak menyadari posisinya sebagai buruh karena istillah tersebut tergantikan oleh istilah karyawan. Di samping itu, imajinasi mengenai buruh atau kaum ploretariat ini seringkali dibayangkan sebagai orang yang bekerja fisik, melakukan pekerjaan kasar. Di zaman kecanggihan teknologi pekerjaan kasar tersebut dapat digantikan oleh mesin dan manusia bekerja menggunakan otaknya sebagai operator. Namun pada dasarnya, entah melakukan pekerjaan kasar atau tidak status mereka yang bekerja pun tetap buruh. Yasraf Amir Piliang memilih istilah Cognitariat untuk menyebut buruh di era digital.
Lirik “ngalahin datu sik belek-belek ongkatne” menggambarkan modeldemokrasi tandingan. Tegining-teganang melantangkan suaranya melawan penguasa atas dasar ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap penguasa yang lalim, yang bertindak semena-mena menzalimi rakyatnya.
Teknologi digital telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi rakyat dalam menyuarakan pendapatnya, yang pada gilirannya memperkuat pelaksanaan demokrasi. Melalui media sosial, platform diskusi daring, serta berbagai aplikasi partisipatif, masyarakat kini dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi, kritik, maupun dukungan terhadap kebijakan publik secara langsung dan terbuka. Tegaknya demokrasi di media digital hanya dapat terwujud jika setiap individu memiliki akses yang sama terhadap media digital dan media tersebut tidak dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kepentingan tertentu. Tanpa pemerataan akses dan kepemilikan yang inklusif, media digital justru berpotensi memperkuat ketimpangan informasi dan dominasi opini oleh kelompok elite. Ketimpangan ini dapat menghambat partisipasi publik yang setara dan melemahkan fungsi deliberatif dalam demokrasi digital.
Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya kecenderungan pemerintah untuk membatasi kebebasan berekspresi dengan membungkam media yang menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan-kebijakan publik. Tindakan ini dapat berupa tekanan politik, pemblokiran akses digital, hingga kriminalisasi jurnalis dan aktivis yang vokal. Hal itu menjadi bukti bahwa, Pemerintah takut kepada Tegining Teganang : Rakyat berteriak lantang menyuarakan hak-haknya.
Sumber Pustaka :
[1] Demokrasi Dan Masyarakat Sipil Di Dunia Ketiga : Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir ; Jenis: Monograf ; Author: Haynes, Jeff ; ISBN: 979-461-345-2 ; Edisi: Ed.1.
[2] Nurasih, W., & Witro, D. (2021). Demokrasi Hibrid: pemikiran yasraf amir piliang tentang demokrasi indonesia di era digital. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 11(1), 175-194.
[3] Piliang. Y.A. 2020. Setelah Dunia Dilipat. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
[4] Syaebani, M. I., Yuwono, U., & Ekosiwi, E. K. (2023). Problem alienasi sebagai akibat ketakterwakilan di dalam masyarakat: Analisis pemikiran matematika sebagai ontologi Alain Badiou. Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial, 7(1), 31-41.
[5] Piliang, Yasraf Amir. 2017. Dunia yang Berlari: Dromologi, Implosi dan Fantasmagoria. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
Tentang Penulis
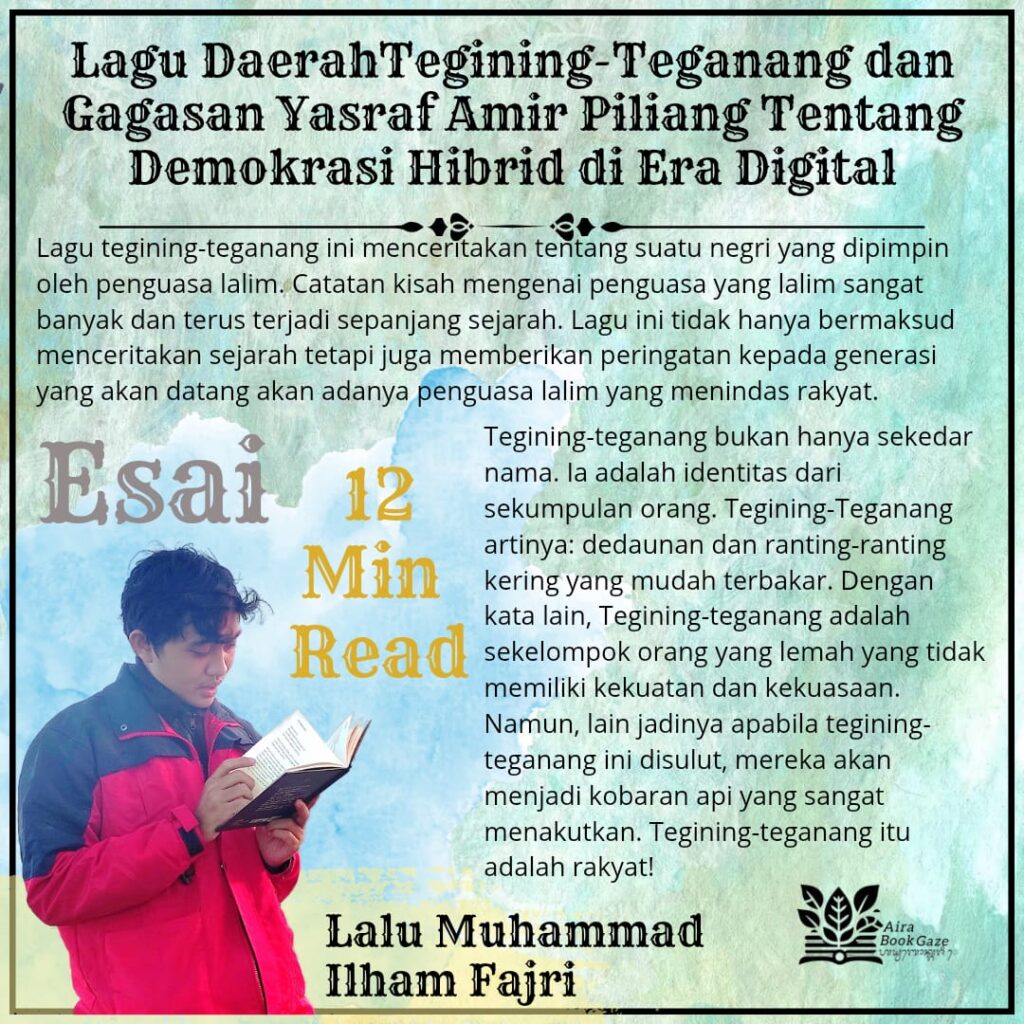
Lalu Muhammad Ilham Fajri, menyelesaikan studi di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selama berkuliah, aktif di Komunitas Literasi Taman Wacana. Kini tinggal di Praya Lombok Tengah dan sedang mengembangkan Aira Book Gaze. Dapat dihubungi melalui sosial medianya : Instagram @lmif81.